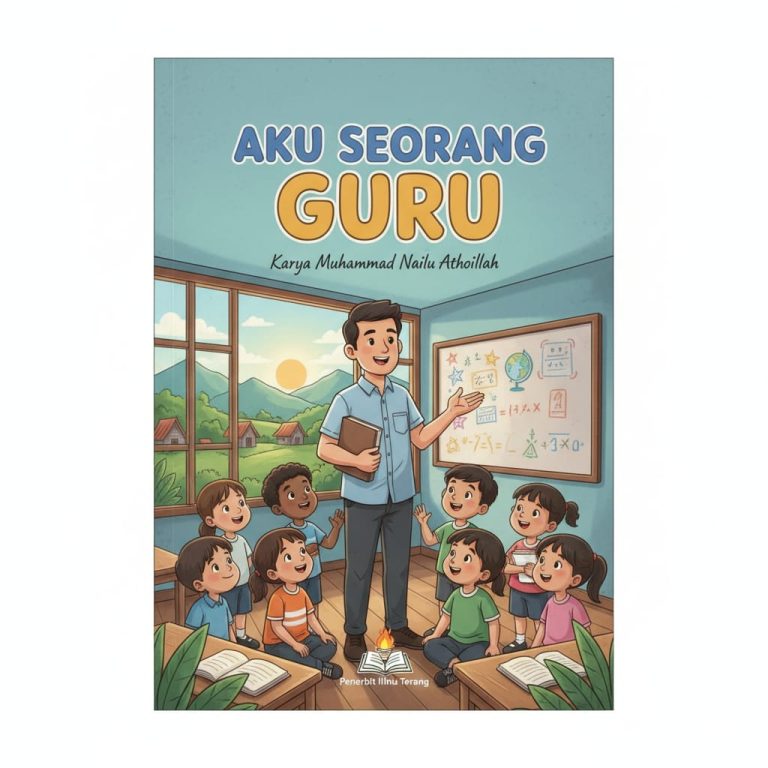Mengajar adalah pengalaman yang penuh makna sekaligus tantangan. Bagi saya, mengajar lebih dari sekadar mentransfer ilmu, melainkan juga proses pembelajaran dua arah di mana baik siswa maupun pengajar sama-sama tumbuh bersama. Sebab, hakikat mengajar adalah belajar tanpa henti. Setiap pertemuan dengan para siswa selalu memberikan pelajaran baru, baik tentang materi ajar maupun cara berinteraksi dengan latar belakang dan karakter mereka yang beragam. Layaknya cermin, setiap respons dan keunikan mereka memantulkan refleksi diri, mendorong saya untuk terus merefleksikan metode dan pendekatan, sekaligus mengingatkan bahwa ruang kelas adalah taman tempat benih pengetahuan dan karakter bertumbuh bersama.
Terlebih mengajar di lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan pesantren. Latar belakang santri yang beragam justru memberi warna tersendiri dalam perjalanan mengajar saya. Ada santri yang berasal dari keluarga religius dengan orang tua yang ahli di bidang ilmu keislaman, yang turut memengaruhi cara berpikir kritis anaknya. Di sisi lain, ada juga yang datang dari latar belakang yang lebih sederhana, bahkan cenderung abangan. Tugas saya adalah memastikan bahwa setiap santri mendapat perhatian yang setara dan dapat merasakan manfaat dari setiap pelajaran yang disampaikan.
Jika ditoleh ke belakang, sekedar flashback, mengajar adalah pengalaman yang menakutkan. Saat pertama kali diberi kesempatan mengajar, jujur saya merasa belum sepenuhnya siap. Saya sadar bahwa besar sekali tanggung jawab untuk bisa menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Apalagi dihadapkan pada siswa-siswi generasi Gen-Z yang kritis, kreatif, dan terhubung secara global. Mereka bisa dengan mudah mempertanyakan, “Bu, apa sih relevansi materi pelajaran ini untuk kehidupan kami?” Bila saya tidak bisa memberikan alasan yang kuat, motivasi mereka bisa saja serta-merta anjlok. Inilah tantangan nyata menjadi guru yang tidak hanya wajib menguasai materi, tetapi juga harus mampu menjadi “penerjemah” yang menjembatani ilmu dengan konteks kehidupan nyata para siswa. Alhasil, mengajar menjadi tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter dan empati.
Kendati dihadapkan pada pengalaman mengajar yang sedemikian pelik, keinginan bapak saya yang ingin sekali melihat anak perempuannya memiliki pengalaman mengajar, menjadi penyemangat tersendiri. Latar belakang ayah sebagai seorang guru agama di madrasah, ditambah keyakinannya pada luhurnya nilai sebuah pengabdian melalui mengajar, akhirnya menguatkan langkah saya. Seiring waktu, saya menyadari bahwa mengajar tidak hanya mengandalkan keahlian teknis, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan menghargai kebutuhan serta minat setiap siswa.
Di sini, di madrasah berbasis pesantren ini, saya pun belajar banyak mengenai fakta bahwa mendidik bukan hanya tentang menyampaikan materi akademik, tetapi juga tentang memotivasi santri untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi sesama. Saya dituntut untuk mampu mengembangkan pendekatan holistik, menggabungkan pelajaran akademis dengan pendidikan karakter dan spiritual. Tentu saja dengan diimbangi usaha untuk terus bisa mengambil kesempatan untuk mengembangkan diri.
Mengajar adalah seni yang membutuhkan kesabaran, kreativitas, dedikasi, serta kerendahan hati untuk terbuka terhadap kritik dan saran. Di era digital seperti sekarang, mengajar memiliki tantangan unik. Saya sering terlibat dalam proses belajar-mengajar yang tidak banyak bergantung pada gawai atau perangkat digital. Meski teknologi tetap digunakan sebagai pendukung sesuai kebutuhan, sebagai pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, saya percaya bahwa sejarah pada dasarnya adalah seni bertutur. Mengajarkan sejarah berarti melatih diri menjadi penutur yang baik. Meski terkesan konvensional, selama disesuaikan dengan kebutuhan materi, substansi pembelajaran tidak akan hilang—justru menjadi tantangan yang bermakna.
Di dalam kelas, saya berusaha menghidupkan kembali narasi-narasi masa lampau bukan sebagai rangkaian tahun yang kering makna, tapi sebagai sebuah drama kemanusiaan yang sarat nilai. Dengan perubahan intonasi, ekspresi, dan pertanyaan-pertanyaan reflektif, saya mengajak siswa untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga membayangkan dan merasakan konteks zaman lampau yang dicatat dalam sejarah. Saya yakin metode ini akan mampu melatih empati dan imajinasi historis mereka, yaitu sebuah keterampilan yang tidak dapat digantikan oleh pencarian informasi instan di internet. Justru di tengah banjir informasi digital, kemampuan untuk menyaring, memahami alur kisah, dan mengambil hikmah dari sebuah ceritalah yang menjadi kunci. Tantangan terbesarnya adalah menjaga api ketertarikan itu tetap menyala, membuktikan bahwa kekuatan sebuah tuturan yang disampaikan dengan hati dapat menembus kebisingan generasi digital.
Saya sepenuhnya sadar bahwa kemampuan komunikasi dan bertutur saya masih perlu terus diasah. Namun, komitmen dan tanggung jawab inilah yang mendorong saya untuk tak berhenti belajar. Semoga dari ketidaksempurnaan ini, lahir tunas-tunas penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijak memaknai setiap jejak peradaban. Itulah harapan terbesar yang menjadi pemacu semangat. Semoga setiap langkah ini diberkahi dan diridai-Nya. Aamiin.