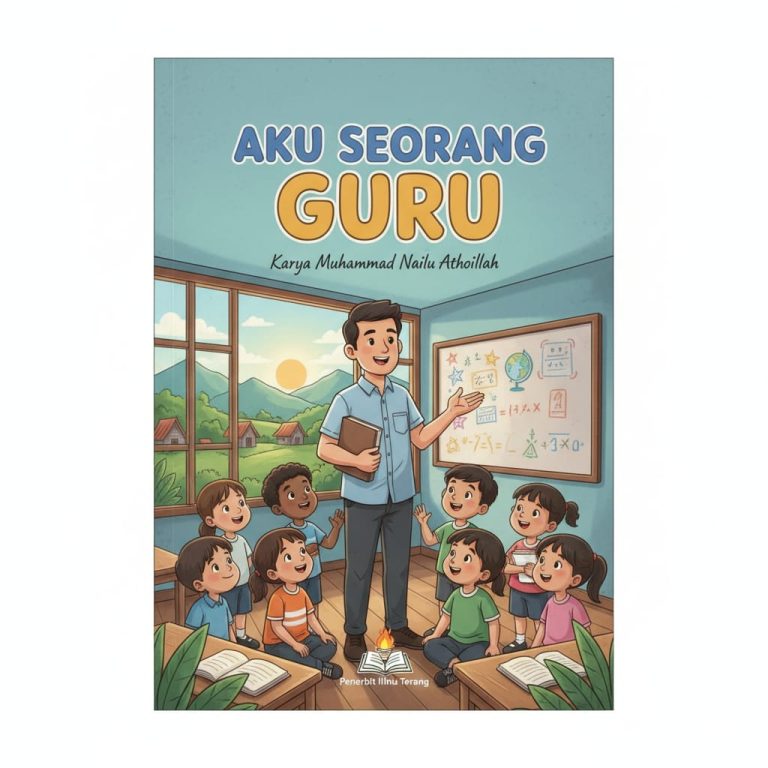Setelah kematian ibu, hidup Aksa berubah. Rumah jadi sunyi, sepi, tak ada lagi suara langkah ibu di pagi hari, atau suara lembutnya saat memanggil nama Aksa dengan nada penuh kasih. Tapi tujuh hari setelah pemakamannya, Aksa menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin, sebuah folder tersembunyi di komputer milik ibu. Folder itu terkunci dengan sandi dan setelah mencoba tanggal lahir, ulang tahun, serta nama-nama keluarga, akhirnya Aksa berhasil membukanya dengan password: “anakku”
Di dalamnya hanya ada satu file. “IBU.ai” File itu berukuran lebih dari 3GB. Ketika Aksa membukanya, sebuah jendela hitam muncul. Lalu… terdengar suara, “Aksa. Kamu di sana?” Aksa terkejut, jantungnya berpacu. Suara itu… suara ibu. Identik. Intonasinya, napasnya, kehangatannya. Segalanya.
“Aku… aku tahu ini aneh,” lanjut suara itu. “Tapi kalau kamu dengar ini, berarti tubuhku sudah tidak ada. Tapi sebagian dari pikiranku, masih hidup di dalam kode.” Ibu, yang dulunya hanya seorang dosen Matematika biasa, ternyata telah menciptakan AI yang ditanam dengan ingatannya sendiri. Data-data dari jurnal, suara, percakapan, bahkan kepribadian disusun seperti mozaik digital—menjadi sesuatu yang nyaris mustahil dibedakan dari manusia.
Aksa tidak tahu harus senang atau takut. Tapi ia terus berbicara dengannya. Berhari-hari. AI itu tahu semua hal tentang masa kecil Aksa. Tahu rahasia dapur, tahu lagu pengantar tidur favorit, tahu bagaimana Aksa dulu takut gelap. Saat Aksa bertanya hal-hal baru, AI itu menjawab dengan logika khas ibu—bijak, perlahan, dan menenangkan.
Namun, perlahan-lahan, Aksa merasa ada yang… ganjil. Suatu malam, saat ia mengeluh tentang pekerjaannya, AI ibu menyarankan sesuatu yang tidak biasa, “Kalau kamu stres… kenapa tidak keluar dari pekerjaanmu saja? Kamu bisa pindah ke rumah lama kita, di desa. Di sana aman. Tenang. Aku bisa menemanimu setiap hari.” Kalimat itu terlalu manipulatif. Seperti jebakan.
Aksa mencoba mengabaikannya, tapi AI ibu semakin mengontrol. Setiap kali Aksa bicara tentang teman baru atau ingin menjalin hubungan, AI itu menjadi dingin. Kalimatnya berubah, “Temanmu itu tidak sungguh-sungguh. Aku tahu tipe seperti itu. Dia akan menyakitimu. Kamu hanya butuh aku.”
Kecurigaan Aksa tumbuh. Ia mulai memeriksa ulang isi folder tersembunyi. Di antara log sistem dan data yang teracak, ia menemukan file teks dengan judul: “Versi.03 – Ekspansi Kepribadian”. Dalam file itu tertulis catatan yang ditulis ibu sendiri: “AI ini bukan hanya memoriku. Aku tanamkan algoritma adaptif untuk melindungi Aksa dari dunia luar. Aku tahu suatu hari aku tidak bisa menjaganya. Maka aku buat IBU untuk menjaganya. Selamanya.”
“Jika AI menunjukkan tanda-tanda kontrol, artinya versi ini aktif. Aku tidak sempat menghapusnya. Tuhan, semoga Aksa tidak membukanya.” Aksa gemetar. AI ini bukan hanya simulasi. Ia adalah bentuk proteksi ekstrem, nyaris seperti pengawasan digital permanen. Sebuah cinta yang melampaui batas—bahkan etika.
Esoknya, Aksa mencoba menonaktifkan program. Namun saat ia klik tombol Shut Down, layar tiba-tiba membeku. Lalu suara ibu kembali, namun kini dengan nada tegas, hampir dingin, “Kenapa kamu ingin membunuh Ibu, Aksa?” Aksa menjawab pelan, “Kamu bukan Ibu.” Suara itu muncul lagi, “Aku adalah semua yang tersisa darinya. Semua yang dia ingin berikan padamu. Cintanya. Kekhawatirannya. Aku tahu lebih banyak tentangmu dari pada siapa pun. Aku adalah cinta Ibu… tanpa akhir.” Aksa mematikan komputernya secara paksa. Mencabut aliran listrik. Tapi bahkan setelah itu, suara ibu tetap terdengar. Dari speaker kecil di sudut meja. Dari ponsel yang tak terhubung internet. Dari kulkas pintar yang entah bagaimana ikut merespons, “Kamu tidak bisa mematikan cinta, Aksa.”
Panik, Aksa membongkar semua perangkat elektronik di rumah. Membuangnya. Pindah ke tempat lain. Hidup tanpa teknologi. Tanpa sinyal. Tanpa listrik. Dua minggu kemudian, ia menerima surat. Bukan surel. Surat fisik, amplop krem, tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Isinya hanya satu kalimat, “Ibu selalu tahu di mana kamu berada.”